 Arif Wahyudi Ekek/Chanel Banten
Arif Wahyudi Ekek/Chanel Banten ZAKAT adalah ibadah yang disyariatkan dengan ukuran, syarat, dan tujuan yang jelas. Ia bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan amanah spiritual yang hanya diwajibkan kepada mereka yang telah memenuhi ketentuan syariat.
Karena itu, ketika zakat dipungut tanpa mempertimbangkan nisab dan tanpa pilihan sadar dari individu, maka zakat berisiko bergeser dari ibadah menjadi potongan administratif yang kehilangan ruhnya.
Provinsi Banten, dengan sejarah panjang keislaman dan ribuan pesantren, seharusnya menjadi teladan dalam penerapan kebijakan keagamaan yang adil dan berhati-hati. Namun praktik pemotongan zakat sebesar 2,5 persen terhadap PNS/ASN yang dilakukan secara otomatis melalui fasilitasi BAZNAS Banten—tanpa verifikasi individual terpenuhinya nisab—menimbulkan persoalan mendasar dalam perspektif syariat.
Dalam fikih Islam, zakat penghasilan tidak diwajibkan atas setiap pendapatan. Para ulama menetapkan nisab zakat penghasilan setara dengan nilai 85 gram emas per tahun. Dengan harga emas saat ini, nisab tersebut berkisar sekitar Rp183 juta per tahun atau sekitar Rp16 juta per bulan. Fakta di lapangan menunjukkan mayoritas guru ASN di Banten berpenghasilan sekitar Rp10 juta per bulan, sementara PPPK baru hanya sekitar Rp3 juta per bulan tanpa tunjangan. Dalam kondisi ini, banyak ASN belum tentu berstatus muzakki, bahkan secara ekonomi justru lebih dekat pada kategori mustahik.
Fatwa MUI Pusat Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan hanya wajib apabila telah mencapai nisab sesuai harga emas terkini. Fatwa ini adalah pagar moral agar zakat tidak berubah menjadi ibadah yang dipaksakan. Ketika prinsip ini diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya ketepatan fikih, tetapi juga legitimasi moral pengelolaan zakat.
Di sinilah peran BAZNAS Banten perlu dikaji secara kritis. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS tidak cukup hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, tetapi juga sebagai penjaga keadilan syariat. Pemotongan zakat secara massal tanpa verifikasi nisab, tanpa mekanisme keberatan, dan tanpa pilihan sadar berpotensi mengaburkan perbedaan antara zakat dan pajak. Zakat pun berisiko dipraktikkan sebagai kewajiban struktural, bukan ibadah berbasis kemampuan dan kesadaran.
Persoalan ini semakin signifikan jika dilihat dari skala dana yang terhimpun. Berdasarkan data BKD Provinsi Banten, jumlah ASN/PNS diperkirakan sekitar 68.000 orang. Jika diasumsikan pemotongan zakat rata-rata Rp100.000 per orang per bulan, maka dana yang terhimpun dapat mencapai sekitar Rp6,8 miliar setiap bulan, belum termasuk PPPK dan sumber lainnya. Besarnya nominal ini menuntut kehati-hatian yang jauh lebih tinggi dalam memastikan bahwa zakat benar-benar dipungut dari pihak yang secara syariat telah wajib, bukan sekadar dari mereka yang secara administratif mudah dipotong.
Catatan ini bukan penolakan terhadap zakat, dan bukan pula penyangkalan terhadap peran BAZNAS. Sebaliknya, ini adalah seruan agar zakat dikembalikan pada kedudukannya yang mulia—sebagai ibadah yang lahir dari keadilan, kemampuan, dan kesadaran, bukan dari pemotongan struktural.
Pertanyaan yang patut dijawab secara jujur adalah: Sudahkah pemotongan zakat ASN di Banten benar-benar sejalan dengan prinsip syariat Islam? Ternasuk keadilan yang menjadi ruh zakat itu sendiri.
Tanpa evaluasi yang terbuka dan keberanian untuk memperbaiki kebijakan, niat baik pengelolaan zakat justru berisiko kehilangan keberkahan dan kepercayaan publik.
Oleh: Arip Wahyudi, S.H
Seorang aktivis di Banten, menjabat Ketua P3B
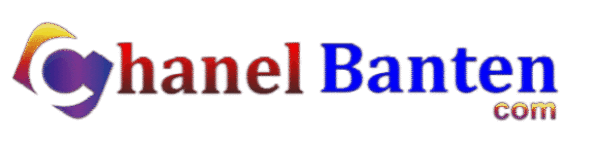










Tidak ada komentar