 Ilustrasi trailer film kisah Saijah dan Adinda yang diangkat ke layar lebar/tangkapan layar
Ilustrasi trailer film kisah Saijah dan Adinda yang diangkat ke layar lebar/tangkapan layar JAKARTA – Ketimpangan sosial sangat dirasakan masyarakat Banten di era kolonial. Para pejabat hidup penuh dengan kemewahan, sementara rakyatnya menderita.
Kontrasnya ketimpangan itu di ceritakan Eduard Douwes Dekker dalam sebuah karya sastranya berjudul Max Havelaar dengan nama pena Multatuli. Melalui karya itu, mata Eropa terbuka dengan betapa buruknya sistem kolonial dan kekejaman di Banten.
Multatuli dalam karyanya mengisahkan pula kisah cinta dua anak remaja Saijah dan Adinda yang mengalami penderitaan dampak buruknya sistem kolonial saat itu.
Kisah di mulai pada periode tanam paksa yang digulirkan sejak tahun 1830. Di mana kebijakan itu sangat mencekik rakyat Banten. Penderitaan rakyat Banten ditambah pula oleh kesemena-menaan Adipati Lebak dan Demang Parangkujang yang sungguh memuakkan.
Petani dibebani pajak tinggi. Mereka juga merampas ternak dan hasil bumi milik rakyat seenaknya. Bahkan para penguasa membuat hukum berdasarkan aturan mereka sendiri.
Tangan kekuasaan
Para birokrat pribumi adalah tangan kekuasaan kolonial di Banten. Lewat para penguasa pribumi pemerintah Belanda menjalankan kekuasaan mereka di tanah jajahan.
Kisah Saijah dan Adinda sendiri oleh Multatuli digambarkan di tengah penderitaan petani di Banten. Di mana Saijah kecil sangat menyayangi kerbau miliknya seperti sahabat sendiri. Namun kebahagiaan itu di renggut.
Tak peduli dengan kesedihan Saijah, para begundal-bengundal tengkik suruhan Bupati Lebak dan Demnang Parungkujang beberapa kali mengambil paksa kerbau Saijah. Melawan kala itu adalah konyol, karena berani melawan sama saja menyerahkan nyawa.
Pemerasan terjadi terus dan terus. Keluarga Saijah diliputi ketakutan dan bahkan sampai jatuh miskin karena tak punya apa-apa lagi. Seluruh harta miliknya habis kuras oleh Demang Parangkujang.
Anggota keluarga Saijah yang paling terpukul akibat perlakuan semena-mena itu adalah ibunya yang jatuh sakit. Ironinya Ibunya lalu meninggal. Keluarga Saijah kian menderita, karena setelah ibunya meninggal ayahnya stres dan pergi dari kampung. Setelah itu, ayah Saijah tak pernah kembali.
Dalam selimut kesedihan, Saijah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda. Dia menjalin kasih dengan Adinda sahabatnya sejak kecil. Saijah dewasa lalu merantau ke Batavia bekerja menjadi pengurus kuda dan pelayan pada seorang Belanda.
Hubungan cinta Saijah dengan Adinda terus berlanjut meski terpaut jarak. Selama bekerja dalam perantauannya Saijah mengumpulkan uang untuk kelak melamar kekasih tercintanya Adinda.
Akhirnya setelah bertahun-tahun Saijah kembali ke kampungnya dengan harapan disambut oleh cinta. Namun ironinya bukan cinta yang di dapat, melainkan kekecewaan. Di kampung halaman, Saijah mendapati Adinda dan ayahnya sudah tak ada di kampung itu. Ayah dan anak itu lari karena tak bisa membayar pajak dari penguasa.
Kejar keluarga Adinda
Saat itu, Adinda dan ayahnya dikabarkan pergi bergabung untuk melawan tentara Belanda di Lampung. Tak putus asa, dia mengejar sang kekasih dengan mencoba menapaki jejak Adinda dan keluarganya.
Hanya saja setelah menyebrangi lautan, upaya pencariannya berbuah pahit. Dia menemukan sang kekasih Adinda meninggal dalam sebuah pertempuran. Tubuhnya penuh luka, kejamnya Adinda juga diperkosa tentara Belanda.
Menyaksikan sang kekasih meninggal mengenaskan, Saija murka. Dengan penuh rasa amarah dan putus asa pemuda itu menerjang barikade tentara Belanda yang menghunus bayonet. Dia menghujamkan tubuhnya pada bayonet serdadu yang tajam.
Adinda dan Saijah tewas dalam peluh kekejaman. Cinta suci dua insan dari rakyat jelata itu kandas di tangan kekejamnya kolonialisme bangsa asing dan keserakahan pejabat dari bangsa mereka sendiri.
Editor: Galuh Malpiana
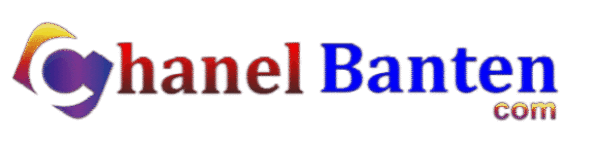










Tidak ada komentar